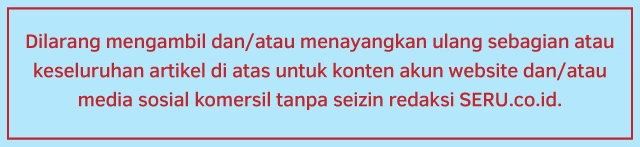Oleh: Dr. Sholikh Al Huda, M. Fil. I
Dosen Filsafat Sekolah Pascasarjana UM Surabaya
Setiap kali ribuan orang turun ke jalan, kita seperti sedang menonton sebuah drama sosial dengan alur yang sulit ditebak. Awalnya, panggung itu dipenuhi yel-yel, spanduk, dan semangat damai untuk menyuarakan aspirasi. Namun, tak jarang, adegan berubah begitu cepat: ban terbakar, pagar dirusak, dan aparat bentrok dengan massa. Demonstrasi yang diniatkan sebagai pesta demokrasi menjelma jadi perayaan anarki.
Pertanyaannya: apa yang membuat kerumunan begitu mudah berbalik arah?
Hilangnya Identitas Individu
Gustave Le Bon, pemikir Prancis pada akhir abad ke-19, menjelaskan bahwa kerumunan punya logika sendiri. Dalam bukunya The Crowd: A Study of the Popular Mind (1895), ia menyebut individu yang masuk ke dalam massa akan kehilangan identitas personalnya. Proses ini disebut deindividuasi.
Orang yang biasanya tenang, rasional, bahkan taat hukum, bisa tiba-tiba nekat melempar batu hanya karena merasa dirinya “tak terlihat” di balik ribuan orang lain. Anonimitas memberi rasa aman semu: tanggung jawab personal lenyap, digantikan identitas kolektif yang liar.
Penularan Emosi
Kerumunan, kata Le Bon, bekerja dengan mekanisme penularan emosi. Emosi menyebar lebih cepat daripada logika. Satu orang yang menyalakan api atau berteriak lantang bisa memicu gelombang marah, frustrasi, bahkan keberanian instan. Dalam hitungan menit, energi kolektif meledak.
Fenomena ini menjelaskan mengapa demonstrasi yang awalnya damai bisa seketika ricuh, meski tidak pernah direncanakan. Emosi massa bergerak seperti arus deras yang sulit dibendung.
Sugesti dan Simbol
Kerumunan juga sangat mudah disugesti. Mereka tidak bergerak oleh analisis panjang, melainkan oleh simbol, imaji, dan slogan sederhana. Kata-kata singkat seperti “revolusi sekarang!” atau “lawan tirani!” sering kali lebih ampuh daripada penjelasan panjang soal kebijakan.
Itulah mengapa provokator meski jumlahnya kecil bisa menggiring ribuan orang. Kerumunan ibarat rumput kering: cukup satu percikan api, apinya menjalar ke mana-mana. Membakar ban atau merusak pagar pun dianggap simbol heroik, meski sejatinya merugikan publik.
Konteks Indonesia
Dalam realitas Indonesia, demo anarkis kerap dipicu oleh akumulasi kekecewaan: soal upah buruh, kenaikan harga, kebijakan kontroversial, atau krisis politik. Namun, sebagaimana dikatakan Le Bon, faktor struktural hanyalah latar belakang. Yang lebih menentukan adalah bagaimana psikologi massa bekerja di lapangan.
Atmosfer emosional, rasa aman di balik kerumunan, dan kekuatan sugesti oratorlah yang mengubah jalan damai menjadi panggung rusuh.
Kritik atas Le Bon
Pandangan Le Bon bukan tanpa kritik. Ia sering dianggap terlalu pesimistis karena menggambarkan kerumunan seolah selalu irasional dan destruktif. Padahal sejarah menunjukkan banyak aksi massa justru tertib dan melahirkan perubahan positif: gerakan kemerdekaan, reformasi 1998, hingga aksi solidaritas kemanusiaan.
Namun, tak bisa dipungkiri, potensi destruktif selalu mengintai. Kerumunan memang bisa menjadi energi perubahan, tetapi juga bisa berubah menjadi badai anarki.
Pelajaran bagi Kita
Pelajaran penting dari teori Le Bon adalah: mengelola demo bukan hanya soal barikade aparat. Yang lebih penting adalah memahami psikologi massa. Bagaimana mengatur komunikasi, meredam emosi kolektif, dan mencegah provokasi kecil menjadi kerusuhan besar.
Aksi massa adalah arena simbolik. Karena itu, pemerintah, aparat, dan koordinator lapangan harus cermat memainkan simbol dan bahasa agar aspirasi tidak berubah jadi amarah.
Demo adalah hak warga negara, bagian dari demokrasi. Tetapi ia juga cermin betapa tipis jarak antara aspirasi dan anarki. Kerumunan selalu punya dua wajah: bisa menjadi energi konstruktif yang mendobrak perubahan, atau energi destruktif yang mengoyak tatanan.
Maka, pertanyaannya kini bukan sekadar “apakah rakyat boleh demo?”, melainkan: apakah pemerintah siap mendengar sebelum suara rakyat berubah menjadi teriakan marah di jalanan? Sebab sekali kerumunan menjelma amuk, yang terbakar bukan hanya ban di aspal, melainkan juga kepercayaan publik pada negara. (*)