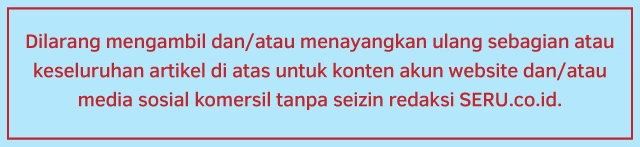Malang, SERU.co.id – Penggunaan istilah “Nataru” kembali memicu polemik di ruang publik. Sejumlah tokoh menilai akronim Natal dan Tahun Baru itu problematis karena berpotensi mengaburkan makna hari besar keagamaan. Namun, pakar bahasa menyebut istilah tersebut sah secara linguistik tetapi perlu mempertimbangkan sensitivitas sosial dalam masyarakat majemuk.
Sastrawan nasional, Okky Madasari secara terbuka mempertanyakan pihak pertama kali meresmikan istilah tersebut. Ia mengaku heran, mengapa media massa menggunakannya secara serempak, seolah tanpa refleksi kritis.
“Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga medium kekuasaan yang dapat melahirkan ketidakadilan, intoleransi dan diskriminasi. Banyak praktik diskriminatif kerap berawal dari bahasa yang dianggap netral dan wajar,” seru mba Okky, sapaannya, dikutip dari instagram pribadinya @okkymadasari, Selasa (30/12/2025).
Istilah Nataru memang sudah digunakan sebelumnya oleh pihak tertentu. Okky menilai, sejak sekitar 2020, media arus utama mulai menggunakannya secara masif tanpa diskusi publik memadai.
Keberatan juga datang dari kalangan politisi. Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Stevanus Christian Handoko menilai, penggunaan istilah Nataru tidak tepat dan berpotensi menyesatkan. Bahkan, menurutnya, ada kecenderungan penistaan terhadap makna hari besar keagamaan.
“Natal adalah perayaan sakral umat Katolik dan Kristen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Natal bukan hanya perayaan kebahagiaan fisik, tetapi momen perenungan iman dan penguatan kasih terhadap sesama,” ujar Stevanus, dilansir dari RRI.
Sebaliknya, Tahun Baru Masehi dipahami sebagai perayaan bersifat sekuler dan tidak terkait langsung dengan ajaran agama tertentu. Penggabungan keduanya ke dalam satu istilah dianggap Stevanus mereduksi kesakralan Natal. Bahkan mencampurkannya dengan perayaan yang secara makna berbeda.
“Jika logika pemenggalan dan penggabungan kata seperti ini diterapkan pada hari besar agama lain, potensi ketersinggungan akan semakin besar. Saya berharap tidak lagi menggunakan istilah Nataru untuk menyebut Natal dan Tahun Baru secara bersamaan,” tambahnya.
Di sisi lain, secara leksikal, akronim “Nataru” sudah ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Nataru didefinisikan sebagai akronim dari Natal dan Tahun Baru, merujuk pada periode hari libur keduanya.
Pemimpin Redaksi (Pemred) SERU.co.id, Rahadi Adnil menilai, penggunaan istilah Nataru secara kebahasaan memang kurang tepat. Namun, ia menekankan, istilah tersebut bukan lahir dari inisiatif media. Melainkan telah lebih dulu digunakan oleh institusi seperti TNI–Polri dan sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Dalam praktiknya, media massa hanya mengutip istilah yang dipakai oleh sumber resmi. Jadi kurang tepat jika penggunaan istilah Nataru sepenuhnya dibebankan kepada media,” kata Rahadi.
Ia menambahkan, faktor keterbiasaan di ruang digital turut berpengaruh. Dimana istilah yang sering digunakan akan membentuk pola pencarian di mesin pencari (SEO). Sementara keterbatasan pilihan kata dan kebutuhan komunikasi ringkas kemungkinan menjadi alasan utama istilah tersebut digunakan oleh institusi negara.
Sementara itu, pakar linguistik, Aprilia Kartika Putri MHum menjelaskan, penutur bahasa Indonesia memiliki kecenderungan kuat untuk menyingkat kata atau frasa. Fenomena ini telah lama dikaji oleh para ahli linguistik, salah satunya De Vries dalam artikelnya Indonesian Abbreviations and Acronyms (1970).
“Kebiasaan menyingkat sudah muncul dari bahasa daerah. Berkembang di era pemerintahan Soekarno dan Soeharto, dunia militer, hingga akhirnya dipopulerkan secara luas oleh media massa,” ungkap dosen linguistik Prodi Sastra Indonesia Universitas Jambi tersebut.
Menurut Aprilia, penyingkatan dilakukan demi efisiensi bahasa agar tidak terus-menerus mengulang frasa sama. Terlebih ketika konteksnya sudah dipahami bersama. Dalam konteks ini, Natal dan Tahun Baru yang waktunya berdekatan kemudian diringkas menjadi Nataru.
“Secara struktur bahasa, penyingkatan ini sah dan tidak salah,” jelasnya.
Namun, Aprilia menekankan, bahasa bersifat konvensional. Artinya, makna dan penggunaannya lahir dari kesepakatan sosial yang tidak tertulis. Ketika ada kelompok masyarakat yang merasa tersinggung atau menilai terjadi pengaburan makna sakral, keberatan tersebut patut didengar.
“Media massa memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan berbahasa publik. Jika istilah tertentu dinilai problematis, media seharusnya membuka ruang dialog atau bahkan mempopulerkan alternatif istilah lebih sensitif. Misalnya ‘libur akhir tahun’ atau penyebutan terpisah antara libur Natal dan libur Tahun Baru”, tambahnya.
Perubahan bahasa untuk menghindari diskriminasi, menurutnya, bukanlah hal baru. Dalam konteks global, istilah rasis dalam bahasa Inggris telah lama ditinggalkan. Di Indonesia sendiri, penggunaan kata “Cina” secara resmi diganti menjadi “Tionghoa” melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 demi menghindari muatan diskriminatif.
Kontroversi istilah Nataru pada akhirnya menegaskan satu hal, bahasa tidak pernah netral. Bahasa selalu membawa nilai, kuasa dan sensitivitas. Di tengah masyarakat majemuk, pilihan kata bukan sekadar soal ringkas atau praktis, tetapi juga tentang penghormatan, keberagaman dan kesadaran sosial. (aan/mzm)