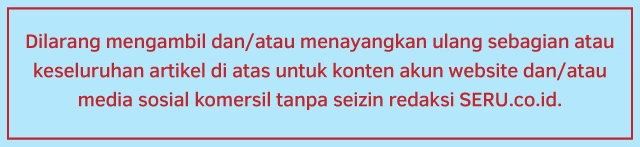Malang, SERU.co.id – Mencuatnya kasus child grooming menyingkap kegagalan kolektif mengenali kekerasan emosional terhadap anak. Dibungkus perhatian, praktik ini kerap luput hingga korban justru disalahkan dan menanggung trauma sendirian. Sejumlah pakar menegaskan child grooming adalah kekerasan berbasis relasi kuasa yang tidak pernah muncul dari persetujuan korban.
Pakar Psikologi dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Ratih Eka Pertiwi SPsi MPsi menegaskan, child grooming merupakan bentuk kekerasan serius. Namun sering luput dikenali karena berlangsung perlahan, sistematis dan melibatkan relasi kuasa yang timpang.
“Pelaku biasanya tampil sebagai sosok yang peduli, baik dan penuh perhatian. Dalam situasi itu, korban bisa merasa nyaman. Bahkan membela pelaku, karena sudah terbentuk ikatan emosional kuat, mirip dengan Stockholm syndrome,” seru dosen Psikologi UMM ini, Selasa (27/1/2026).
Menurutnya, fase awal grooming kerap diabaikan, karena belum menunjukkan kekerasan fisik. Banyak orang baru menyadari adanya kekerasan ketika pelecehan seksual sudah terjadi. Padahal manipulasi emosional telah berlangsung jauh sebelumnya.
“Bahkan meninggalkan dampak psikologis mendalam bagi korban. Ketika kekerasan baru diakui setelah ada kontak fisik, itu artinya kita sudah terlambat melindungi anak,” tegasnya.
Ratih menjelaskan, relasi kuasa menjadi elemen utama dalam praktik child grooming. Terutama ketika pelaku memiliki usia lebih tua, posisi sosial tertentu, atau popularitas yang membuatnya tampak aman. Ketimpangan inilah yang sering berujung pada praktik victim blaming, yakni korban justru diposisikan sebagai pihak bersalah.
“Victim blaming mempersempit ruang aman korban untuk berbicara dan mencari pertolongan. Ini sangat merugikan dan dapat memperparah trauma psikologis,” jelas psikolog ini.
Ia menambahkan, tanda-tanda child grooming bisa dikenali melalui perubahan emosi dan perilaku anak. Seperti menarik diri dari lingkungan sosial, perubahan suasana hati ekstrem, hingga kecenderungan menyimpan rahasia dari keluarga. Di era digital, risiko semakin besar, karena pelaku dapat menjangkau anak melalui media sosial, gim daring dan berbagai platform komunikasi lainnya.
“Jika anak diminta merahasiakan hubungan atau dibuat merasa bersalah saat menolak permintaan orang dewasa. Itu sudah menjadi alarm serius,” tandas Ratih.
Mengapa Pelaku Marah dan Menyangkal?
Spesialis Kedokteran Jiwa, dr Lahargo Kembaren SpKJ mengungkapkan, penyangkalan dan luapan emosi yang kerap ditunjukkan pelaku child grooming. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari pola psikologis tertentu.
“Setidaknya ada empat pola psikologis yang umum muncul pada pelaku child grooming. Pertama, mekanisme pertahanan diri, dimana pelaku menyangkal perbuatannya, agar tidak merasa bersalah. Pelaku tidak mau harga dirinya runtuh dan tidak harus menghadapi kenyataan telah melukai orang lain,” ungkap Lahargo, dikutip dari detikHealth.
Kedua, cognitive dissonance, yakni kondisi psikologis tidak nyaman akibat konflik keyakinan. Terdapat konflik antara “saya orang baik” dengan “saya menyakiti orang lain”. Untuk meredam konflik itu, pelaku memilih menyangkal fakta, menyalahkan korban, atau marah saat dikonfrontasi.
“Ketiga, aspek kontrol dan kekuasaan. Grooming pada dasarnya adalah soal power. Ketika kontrol itu terancam, pelaku dapat bereaksi dengan panik, marah dan meledak-ledak, karena kehilangan posisi dominan,” jelasnya.
Keempat, minimnya empati terhadap dampak yang dialami korban. Pelaku lebih fokus pada dirinya sendiri ketimbang luka psikologis korban. Marahnya pelaku menjadi tanda mekanisme pertahanannya sedang runtuh.
Peran Orang Tua Jadi Kunci Pencegahan
Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia (UI), Prof. Rose Mini Agoes Salim menekankan, pencegahan child grooming harus dimulai dari lingkungan terdekat, terutama keluarga. Ia membagikan sejumlah langkah yang bisa dilakukan orang tua untuk melindungi anak, di antaranya:
- Orang tua perlu memastikan anak merasa aman dan nyaman, baik di rumah maupun di sekolah.
- Selalu menghargai anak dan memberi dukungan, terutama ketika mereka menghadapi masa sulit seperti krisis remaja.
- Beri ruang bagi anak untuk menyampaikan perasaan, pikiran dan keinginannya agar mereka tidak merasa sendirian dan mencari figur lain di luar keluarga.
- Izinkan anak mengeksplorasi minat dan aktivitasnya secara sehat, agar tidak terbiasa menyembunyikan sesuatu dari orang tua.
- Bantu anak membangun komunikasi yang baik di rumah dan di sekolah.
- Dampingi anak memahami konsep dirinya agar tumbuh percaya diri dan tidak bergantung secara emosional pada orang lain.
- Perhatikan perubahan perilaku anak, termasuk jika ia tampak menarik diri atau tidak memiliki teman, lalu cari tahu penyebabnya.
“Perlindungan anak tidak cukup hanya mengandalkan regulasi. Dibutuhkan kepekaan, keberanian dan keterlibatan aktif masyarakat untuk mengkritisi relasi yang tampak normal. Namun sesungguhnya berpotensi membahayakan,” pungkas Rose. (aan/rhd)