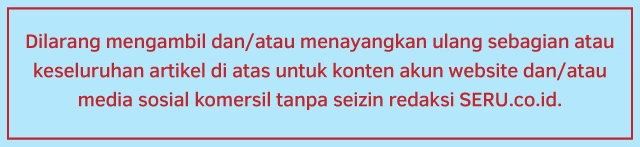Malang, SERU.co.id – Banjir besar kembali melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, menimbulkan kerusakan parah sekaligus penderitaan bagi ribuan warga. Di balik bencana tersebut, persoalan kerusakan lingkungan kembali mencuat dan disorot sebagai salah satu pemicu utama. Guru Besar Mitigasi Bencana Universitas Brawijaya (UB), Prof. Sukir Maryanto menilai derasnya arus banjir membawa batang kayu menjadi indikasi kuat aktivitas penebangan hutan di kawasan hulu.
Menurut Prof. Sukir, fenomena kayu terhanyut dalam jumlah besar hampir selalu berkaitan dengan hilangnya tutupan hutan. Ia menegaskan, deforestasi di Indonesia hingga kini masih menjadi masalah krusial. Standar pengelolaan hutan berkelanjutan dinilai masih berada di bawah rata-rata dunia.
“Berbagai program pembukaan lahan di masa lalu, seperti transmigrasi, perkebunan karet, hingga sawit. Dalam praktiknya banyak mengorbankan hutan alam tanpa perhitungan dampak lingkungan jangka panjang. Pemanfaatan hutan sering kali tidak sesuai dengan desain lingkungan. Akibatnya, banjir terus berulang,” seru Prof. Sukir, Kamis (4/12/2025).
Selain kerusakan hutan, faktor cuaca ekstrem juga memperparah risiko banjir. Prof. Sukir menjelaskan, periode September hingga Februari merupakan fase tahunan cuaca ekstrem di Indonesia. Intensitas hujan tinggi dalam waktu singkat meningkatkan potensi banjir dan longsor di berbagai daerah.
“Dampak bencana seharusnya bisa ditekan jika sistem peringatan dini berfungsi optimal. Di Jepang, ramalan cuaca tersedia secara rinci per jam hingga tingkat wilayah kecil. Disebarluaskan melalui televisi publik, transportasi umum, hingga situs resmi pemerintah,” tambahnya.
Kondisi tersebut, menurutnya, memungkinkan masyarakat melakukan antisipasi lebih cepat dan tepat. Khususnya terhadap potensi hujan lebat, angin kencang, maupun bencana lainnya. Sebaliknya, di Indonesia fungsi informasi dan sosialisasi cuaca masih perlu banyak penguatan.
Prof. Sukir menilai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) perlu memperkuat kolaborasi dengan BRIN, badan geologi, serta perguruan tinggi. Ia menyoroti, lemahnya koordinasi antarlembaga. Akhirnya menyebabkan data dan peralatan pemantauan bencana belum terintegrasi secara maksimal.
Dalam kesempatan sama, ia juga mengungkap, temuan anomali sinyal Magnetic Data Acquisition System (MAGDAS) di Stasiun Cangar milik UB yang muncul berdekatan dengan aktivitas erupsi Gunung Semeru. Menariknya, sinyal besar tersebut tidak terekam di stasiun lain seperti di Malaysia maupun Australia.
“Kalangan akademisi tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peringatan dini kepada masyarakat. Kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Para peneliti hanya berperan pada tahap analisis ilmiah,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan, setiap gunung api memiliki karakter dan perilaku berbeda. Karena itu, penelitian spesifik dan mendalam sangat dibutuhkan untuk memahami pola aktivitas masing-masing gunung.
“Harapannya pemerintah dapat memperketat pengawasan lingkungan dan meningkatkan akurasi sistem informasi cuaca. Kemudian menyeragamkan standar peralatan pemantauan bencana di seluruh lembaga terkait. Langkah ini penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus menekan risiko bencana,” pungkasnya. (aan/mzm)