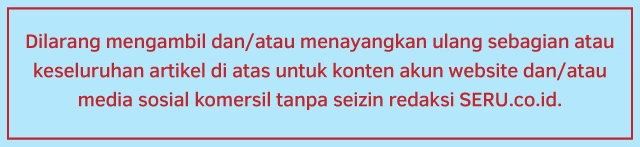*)Oleh: Dr. Sholikhul Huda, M.Fil.I
Ketua Pusat Studi Islam dan Pancasila (PuSIP)
Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya
Pernyataan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi isu ijazah palsu dan wacana pemakzulan Wakil Presiden belakangan ini menegaskan bahwa politik tidak selalu bekerja melalui pidato tegas atau konfrontasi langsung. Dalam konteks Indonesia, politik sering kali bergerak melalui gestur, simbol, serta pernyataan yang samar namun penuh makna. Respons Jokowi yang terlihat ringan dan seolah meremehkan isu ini sebenarnya adalah ekspresi dari strategi komunikasi politik tingkat tinggi.
Melalui pernyataan itu, Jokowi tampaknya sedang tidak hanya merespons isu sempit, tetapi juga mengendalikan lanskap politik yang lebih luas menjelang transisi kekuasaan. Ia sedang bermain dalam kerangka komunikasi yang tidak frontal, tetapi sangat terarah, dengan tujuan mengatur arah perdebatan publik, menenangkan gejolak elite, dan menjaga stabilitas hingga akhir masa jabatannya.
Komunikasi Politik dalam Konteks Krisis Elite
Dalam teori komunikasi politik, sikap diam atau respons singkat terhadap isu besar dikenal sebagai bentuk “strategic silence”. Konsep ini menunjukkan bahwa diam tidak selalu berarti pasif. Sebaliknya, ia adalah bentuk komunikasi yang disengaja sering kali digunakan oleh aktor politik yang memiliki posisi dominan untuk mempertahankan kekuasaan atau menciptakan narasi yang menguntungkan.
Jokowi, dalam hal ini, tampaknya sedang memainkan dua strategi komunikasi sekaligus. Pertama, ia mendelegitimasi isu dengan meresponsnya secara ringan, seolah-olah tidak layak mendapat perhatian serius. Ini penting dalam konteks politik Indonesia, di mana pembentukan opini publik sangat dipengaruhi oleh framing media dan gestur pemimpin.
Kedua, ia mengendalikan arah perdebatan menghindari agar isu ini tidak berkembang menjadi konflik terbuka antar kelompok elite, terutama di tengah kondisi politik yang masih cair pasca-Pilpres 2024.
Isu ijazah palsu dan wacana pemakzulan, apabila tidak dikendalikan, dapat berpotensi menjadi alat delegitimasi terhadap figur-figur tertentu di pemerintahan. Jokowi tampaknya sadar bahwa membiarkan isu ini berkembang tanpa arah justru akan merusak struktur kekuasaan yang ia bangun selama dua periode terakhir.
Stabilitas Menjelang Akhir Kekuasaan
Menjelang akhir masa jabatan, seorang presiden menghadapi dua tantangan utama: memastikan transisi kekuasaan berjalan lancar dan menjaga agar kekuatan politik yang ditinggalkan tidak tercerai-berai. Dalam konteks Jokowi, tantangan ini semakin kompleks karena keberadaan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai Wakil Presiden terpilih, memperpanjang bayang-bayang politiknya di pemerintahan mendatang.
Isu-isu seperti ijazah palsu atau pemakzulan Wapres bisa saja dibaca sebagai gejala awal dari konflik internal koalisi atau resistensi terhadap kontinuitas kekuasaan Jokowi. Dalam konteks ini, pernyataan yang terkesan “dingin” adalah strategi de-eskalasi yang disengaja. Ia bukan hanya menenangkan publik, tetapi juga mengingatkan elite politik agar tidak gegabah memainkan kartu tekanan, yang justru bisa memicu ketidakstabilan sistemik.
Penting diingat bahwa sejarah politik Indonesia dipenuhi dengan episode pemakzulan dan krisis kepercayaan terhadap elite negara. Jokowi tentu tidak ingin masa transisinya dikenang sebagai periode ketidakstabilan atau pengkhianatan elite terhadap kesepakatan politik pasca-Pilpres.
Politik Sinyal: Siapa yang Ditargetkan?
Pernyataan Jokowi juga bisa dibaca sebagai bentuk politik sinyal (signaling politics) yakni komunikasi tidak langsung yang ditujukan untuk aktor-aktor tertentu dalam arena politik. Dalam sistem demokrasi yang masih sangat elite-driven seperti Indonesia, sinyal politik sering kali menjadi lebih penting daripada pernyataan resmi.
Kelompok yang disasar bisa bermacam-macam: elite partai yang merasa tersisih, oposisi yang mencoba mengambil ruang manuver, atau bahkan figur-figur dalam kabinet yang memiliki agenda tersendiri menjelang pembentukan pemerintahan baru. Dengan menempatkan isu-isu tersebut dalam kerangka yang “tidak penting”, Jokowi sebenarnya sedang menutup ruang legitimasi terhadap mereka yang menggunakan isu itu sebagai alat tawar.
Di saat yang sama, ia juga memperkuat posisinya sebagai pengendali politik nasional, bahkan ketika kekuasaan formalnya tengah memasuki fase senja.
Kesimpulan: Politik Diam sebagai Alat Kontrol Wacana
Apa yang tampak sebagai pernyataan biasa sebenarnya adalah bagian dari kalkulasi politik yang matang. Jokowi memanfaatkan politik diam dan komunikasi tidak langsung untuk mempertahankan stabilitas kekuasaan, mengatur arah narasi publik, dan mengingatkan elite bahwa ia belum sepenuhnya meninggalkan panggung kekuasaan.
Dalam sistem politik yang masih sangat dipengaruhi oleh figur sentral dan kepemimpinan personal seperti di Indonesia, kemampuan mengatur wacana sama pentingnya dengan membuat keputusan politik. Dan Jokowi, dalam hal ini, menunjukkan bahwa ia tetap merupakan pemain utama dalam permainan tersebut.
Pernyataan ringan yang dilontarkan di depan media bukanlah tanda kepasrahan, melainkan justru bentuk kekuasaan paling halus yakni mengendalikan arah perdebatan tanpa harus terlibat langsung di dalamnya. (*)