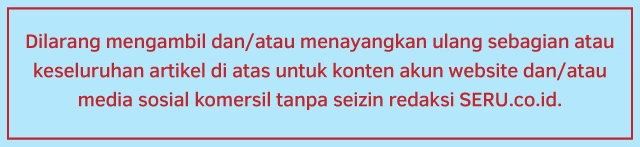*)Oleh: Dr. Sholikhul Huda, M. Fil. I
Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana UM Surabaya dan Ketua Pusat Studi Islam dan Pancasila ( PuSIP)
Sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, tetapi juga arena pertarungan makna yang terus berlangsung di masa kini. Dalam konteks Indonesia, penulisan ulang sejarah selalu menjadi proyek yang sarat kepentingan, baik untuk tujuan edukatif maupun politis. Pertanyaan krusial yang perlu diajukan adalah: Apakah penulisan ulang sejarah Indonesia diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang kritis dan inklusif, atau justru untuk melegitimasi kekuasaan melalui pengendalian narasi sejarah?
Penulisan Sejarah dalam Lintasan Politik Indonesia
Sejak awal kemerdekaan hingga era Reformasi, sejarah Indonesia telah mengalami berbagai perubahan naratif yang mencerminkan dinamika kekuasaan. Di masa Orde Baru, sejarah ditulis dalam kerangka sentralistik yang menekankan peran negara dan militer, sambil menghapus atau mendistorsikan kontribusi kelompok yang dianggap subversif, seperti gerakan kiri. Buku-buku sejarah resmi sekolah dijadikan alat propaganda, bukan wahana pembentukan nalar kritis.
Reformasi membawa angin perubahan. Diskursus sejarah mulai dibuka kembali, termasuk pengakuan terhadap kekerasan negara seperti peristiwa 1965, konflik Aceh, Papua, dan pelanggaran HAM lainnya. Namun, revisi sejarah tersebut tidak sepenuhnya lepas dari tarik-menarik kepentingan: narasi sejarah bisa dibuka, tetapi juga bisa disensor ulang sesuai kepentingan elite yang berkuasa.
Sejarah Sebagai Alat Pendidikan
Dalam kerangka pendidikan, sejarah seharusnya menjadi sarana untuk:
1. Mengedukasi secara kritis, dengan membuka ruang dialog terhadap berbagai versi dan perspektif sejarah.
2. Membentuk karakter kebangsaan yang inklusif, yang mengakui keberagaman pengalaman sejarah masyarakat Indonesia.
3. Mengoreksi distorsi dan bias masa lalu, agar generasi muda tidak mewarisi mitos politik, tetapi pemahaman yang berbasis pada data, kontekstualisasi, dan kemanusiaan.
Penulisan ulang sejarah dalam konteks ini harus melibatkan sejarawan profesional, akademisi, guru, dan komunitas sejarah independen. Kurikulum dan buku pelajaran hendaknya tidak lagi menjadi alat indoktrinasi, melainkan pintu masuk bagi nalar reflektif siswa.
Sejarah sebagai Alat Legitimasi Kekuasaan
Di sisi lain, sejarah juga kerap digunakan sebagai alat untuk mempertahankan atau membentuk legitimasi kekuasaan. Penulisan ulang sejarah dalam konteks ini bukan bertujuan membebaskan pemahaman atas masa lalu, tetapi untuk menanamkan citra politik tertentu di benak publik. Hal ini terlihat dari:
Narasi sejarah yang membesar-besarkan peran tokoh atau rezim tertentu, sembari menutupi atau mengaburkan kontribusi pihak lain.
Penghapusan peristiwa atau kelompok yang dianggap mengganggu stabilitas ideologis negara, seperti sejarah perlawanan rakyat, buruh, atau perempuan.
Penggunaan sejarah sebagai instrumen rekonsiliasi semu, yang memaksa lupa kolektif terhadap tragedi dan kekerasan struktural negara.
Dalam konteks kontemporer, proyek “rekonsiliasi sejarah” sering dibingkai sebagai langkah damai, namun tidak jarang berujung pada impunitas dan penghilangan jejak kebenaran.
Ketegangan dan Persimpangan Arah
Penulisan ulang sejarah Indonesia berada di titik ketegangan antara dua kutub: kebutuhan pendidikan dan kepentingan kekuasaan. Ketegangan ini menciptakan dilema dalam dunia pendidikan, di mana guru dihadapkan pada materi pelajaran yang sering kali sudah “disterilkan” dari konflik sejarah. Sementara itu, di ruang publik, sejarah terus diperebutkan melalui media sosial, monumen, film, dan perayaan nasional.
Apakah kita sedang bergerak menuju sejarah yang lebih demokratis dan reflektif, atau kembali terseret dalam sejarah sebagai mitos kuasa?
Penulisan ulang sejarah Indonesia semestinya tidak semata menjadi proyek birokratik atau simbolik, melainkan bagian dari transformasi kultural menuju bangsa yang berani merefleksikan masa lalunya secara jujur dan adil. Di tengah tantangan politik memori, sejarah harus tetap diposisikan sebagai ruang belajar kolektif—bukan ruang penaklukan narasi. Pendidikan sejarah yang membebaskan akan melahirkan warga negara yang tidak hanya tahu dari mana mereka berasal, tetapi juga ke mana mereka hendak melangkah. (*)