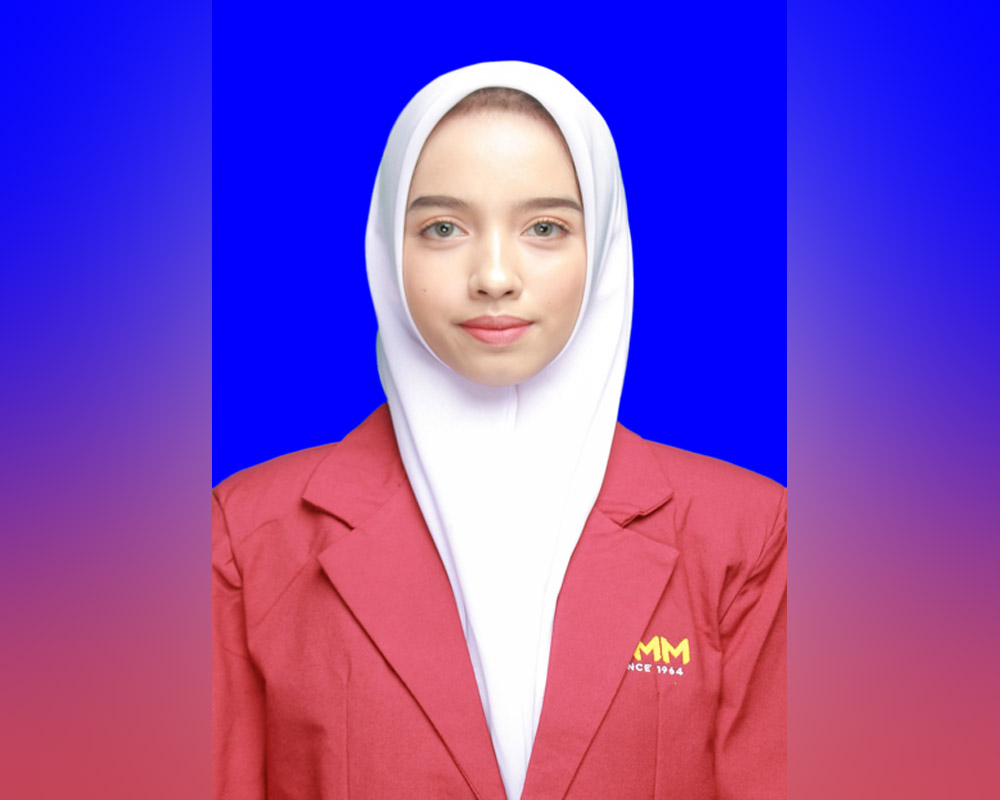Nama: Sofy Syafira
Pendidikan: Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang
Pemilu Amerika Serikat, sebagai salah satu peristiwa politik global paling berpengaruh, tidak hanya berdampak pada arah kebijakan luar negeri dunia, tetapi juga memberi resonansi kuat terhadap dinamika politik domestik di banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satu dimensi yang paling menonjol adalah politik identitas, sebuah fenomena ketika afiliasi terhadap suku, agama, ras, atau kelompok tertentu dijadikan alat mobilisasi politik. Fenomena ini, yang semakin menguat di AS terutama sejak pemilu 2016, turut memantulkan gelombangnya ke Indonesia, memperdalam polarisasi sosial dan politik di tingkat nasional.
Dalam konteks AS, politik identitas menjadi instrumen yang digunakan baik oleh Partai Demokrat maupun Republik untuk mengonsolidasikan basis dukungan. Isu ras, imigrasi, agama, hingga gender dijadikan agenda utama yang memecah opini publik. Retorika populis seperti “Make America Great Again” atau penekanan pada “keragaman dan inklusivitas” bukan sekadar slogan, melainkan narasi besar yang menciptakan “kami” dan “mereka”. Polarisasi inilah yang kemudian menciptakan iklim politik yang tegang dan fragmentatif. Resonansi politik identitas ini dengan cepat menyebar ke negara-negara lain melalui media sosial, budaya populer, dan jaringan diaspora global.
Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tak luput dari pengaruh ini. Polarisasi politik di Indonesia, yang mulai menguat sejak Pilpres 2014 dan memuncak pada Pilpres 2019, memiliki kemiripan pola dengan yang terjadi di AS. Labelisasi seperti “cebong” dan “kampret” mencerminkan pembelahan identitas politik yang bersifat emosional dan cenderung tidak rasional. Pendekatan neo-realisme dalam studi hubungan internasional melihat bahwa sistem internasional—dalam hal ini dominasi dan pengaruh AS—mampu memengaruhi perilaku politik domestik negara lain. AS tidak hanya menyebarkan pengaruhnya lewat kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga lewat narasi politik yang dikonsumsi oleh publik global. Dengan kata lain, politik identitas yang tumbuh subur di AS menjadi model yang secara tidak langsung ditiru atau tercermin dalam konteks domestik negara-negara lain.
Namun, pendekatan utopia menawarkan alternatif dengan melihat pentingnya nilai-nilai global seperti demokrasi inklusif, toleransi, dan solidaritas sebagai kekuatan penyeimbang terhadap fragmentasi identitas. Dalam konteks Indonesia, narasi kebangsaan yang menekankan persatuan dalam keberagaman seharusnya menjadi pondasi kuat dalam merespons pengaruh politik identitas global. Pemilu AS bukan sekadar tontonan politik global, tetapi juga cermin yang memantulkan kecenderungan politik domestik negara lain. Indonesia perlu lebih waspada dalam menyikapi dampak imported polarization ini. Literasi politik, penguatan institusi demokrasi, dan pendidikan kebangsaan menjadi kunci agar politik identitas tidak berubah menjadi konflik identitas. Jika tidak dikelola dengan bijak, resonansi politik identitas dari luar negeri bisa menjadi katalis disintegrasi sosial. Sebaliknya, jika dijadikan pelajaran, Indonesia dapat membangun demokrasi yang lebih matang dan inklusif, yang mampu berdiri kokoh di tengah arus global yang penuh gejolak.